(Catatan Imaginatif tentang Pendidikan)
Oleh: Eko Prasetyo
Pendidikan itu bukan hanya mengisi sebuah keranjang, Melainkan menyalakan sebuah api
(William Butler, Peraih nobel Sastra)
Aku bertemu dengan seorang teman lama. Pria yang kini berposisi mapan sebagai pengusaha. Ia dulu teman satu lingkungan sekolahan. Kebetulan sekolah kami berdekatan. Saya tinggal di sekolah swasta nasional sedang ia menempuh pendidikan di Muhammadiyah. Kebetulan tiap olah raga kami memakai lapangan yang sama. Itulah awal perkenalan dan persahabatan kami. Hanya kemudian setelah lulus saya mulai jarang bertemu denganya. Saya hanya dengar kabar ia kini jadi pengusaha besar. Punya bisnis meubel yang lumayan hingga mampu mengekspor produk. Namanya bahkan tercatat sebagai pengurus partai. Jadi pengusaha kayaknya syarat untuk menjadi apapun di negeri ini. Kedudukan yang kini mengalahkan posisi serdadu.
‘wakh-wakh tak kusangka kita bertemu disini’ begitu tegurnya setelah kami duduk di sebuah tempat makan yang siang itu ramai pengunjung.
‘ya aku juga tak menyangka ketemu kamu disini’
‘bagaimana kabar keluarga? Tanyanya ramah
‘alkhamdulillah. Semua sehat dan kami kini tambah diberi tambahan momongan. Yang nomor dua masih play group dan yang besar baru menginjak kelas 1 SD. Sedang yang ketiga masih usia dua bulan’
‘sama kalau begitu. Yang kecil aku juga masih TK dan yang besar sudah kelas dua’
Kami bicara seperti layaknya masih muda dulu. Kebetulan istrinya adalah seorang yang sangat kukenal. Pengurus organisasi Muhammadiyah yang aktif dan rajin. Dulu kami satu angkatan pelatihan. Namanya masih pelajar belum remaja Muhammadyah. Atau IPM belum IRM.
‘wakh-wakh tak kusangka kita bertemu disini’ begitu tegurnya setelah kami duduk di sebuah tempat makan yang siang itu ramai pengunjung.
‘ya aku juga tak menyangka ketemu kamu disini’
‘bagaimana kabar keluarga? Tanyanya ramah
‘alkhamdulillah. Semua sehat dan kami kini tambah diberi tambahan momongan. Yang nomor dua masih play group dan yang besar baru menginjak kelas 1 SD. Sedang yang ketiga masih usia dua bulan’
‘sama kalau begitu. Yang kecil aku juga masih TK dan yang besar sudah kelas dua’
Kami bicara seperti layaknya masih muda dulu. Kebetulan istrinya adalah seorang yang sangat kukenal. Pengurus organisasi Muhammadiyah yang aktif dan rajin. Dulu kami satu angkatan pelatihan. Namanya masih pelajar belum remaja Muhammadyah. Atau IPM belum IRM.
Ingatan atas istrinya menjadi perbincangan yang saling menyambung. Kini istrinya lebih memilih menjadi ibu rumah tangga yang sibuk memberesi problem rumah. Aku merasa kagum dan salut. Sebuah posisi yang dimuliakan di Venezuela dan negeri-negeri Amerika Latin!
‘memang harus begitu. Dimana-mana banyak penelitian membuktikan seorang anak berhasil biasanya muncul dari model keluarga tradisional. Ibu di rumah dan suami yang bekerja. Kurasa keputusan istrimu itu sangat tepat. Salam untuknya dan aku sangat kagum dengan kesediannya untuk bekerja di rumah
Ia tersenyum dan tampak sangat bangga dengan komentarku. Mungkin ini karena aku juga memutuskan untuk membangun pola seperti itu. Istriku memutuskan untuk tinggal di rumah. Anak-anak kami diasuh olehnya. Memang agak repot tapi ini membuatku tidak kuatir kalau meninggalkan rumah. Anakku berada di tangan ibunya sendiri.
‘jadi apa yang kaulakukan sekarang? Tanyanya sedikit terburu
‘aku sekarang sedang mendirikan sekolah gratis buat anak-anak miskin’ jawabku dengan agak antusias.
Tiap aku bilang tentang sekolah gratis aku selalu saja gembira. Entah mengapa itu seperti aku ditanya tentang bagaimana wajah puteraku. Idam-idaman tentang sekolah gratis jadi harapanku hari-hari ini. Sebuah sekolah yang tidak mengikat siswanya dengan nilai-nilai material. Sebuah pendidikan yang berkaca pada prinsip kerelaan, solidaritas dan keberpihakan. Hingga kini tiap orang bicara tentang pendidikan maka gagasan sekolah gratis itu menarikku untuk berdebat. Kudirikan sekolah gratis untuk menangkal badai materialisme yang kini menghantam banyak sekolah. Sebuah badai mengerikan yang menjepit kemampuan sosial orang-orang miskin. Yang jumlahnya kian hari kian membumbung.
‘wakh luar biasa, kenapa kaudirikan sekolah gratis ini? Tanyanya agak serius
‘begini kawan, aku sendiri kasian melihat banyak orang tua sekitar yang mengeluh tentang biaya pendidikan yang mahal. Beberapa anak memutuskan untuk berhenti sekolah karena biaya. Padahal kau dan aku bisa seperti sekarang karena sekolah. Sekolah itu tangga kita untuk naik kelas sosial yang lebih tinggi. Jika tanpa sekolah pasti kita semua ini akan tetap seperti dulu. Engkau dan aku hanya berdiam di dusun yang sekarang hampir berisi orang-orang tua. Aku akan meneruskan usaha kedai ayahku dan kau hanya menjadi pegawai meneruskan ayahmu juga. Sekolah kawan yang merubah kau dan aku’
Kusiram ceramahku yang biasa kuberikan di berbagai forum. Ingin kuingatkan kata banyak ahli pendidikan tentang daya dobrak sebuah pendidikan. Tanpa pendidikan mungkin Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Tan Malaka hanya menjadi penduduk kolonial. Yang tidak akan berfikir tentang sebuah nation dan gagasan soal kedaulatan. Pendidikan mengenalkan mereka tentang identitas bahkan ideologi sebuah bangsa. Tanpa sekolah semua itu mungkin hanya barang asing yang tidak akan mereka kenali. Kini aku ingin sebagaimana pemerintahan kolonial dulu yang mengenalkan pendidikan kemanusiaan sejak dini. Bukan hanya gratis tapi juga memberi mereka atlas tentang harga diri sebuah bangsa dan arti sebuah kedaulatan. Tapi aku sengaja memendam harapan ini di hadapan kawanku yang lama sekali tak kutemui. Aku bahkan ingin sekali mendengar tanggapanya
‘aku setuju dengan pertimbanganmu. Kau tahu sendiri aku sangat pragmatis. Bahkan dalam segala hal. Anakku kini kusekolahkan di sekolah terbaik dengan biaya yang sangat mahal. SPP nya sebulan mencapai 350 ribu rupiah. Tapi kalau kusekolahkan ke sekolah murah pastilah kau bisa perkirakan bagaimana kualitasnya. Kalau aku secara pribadi berpandangan semua pendidikan butuh biaya. Dan itu harus ditebus dengan biaya mahal. Tapi tak semua orang punya pandangan sama denganku bukan?
Ia lontarkan pertanyaan itu ke arahku. Seperti sebuah lemparan sarung tinju yang harus kukenakan. Aku mengenalnya sangat lama. Kawanku ini dulu anak seorang guru yang sederhana. Sekolah Muhammadiyah kebetulan dekat dengan rumah kami. Sebuah lembaga pendidikan yang berisi banyak orang-orang tak mampu. Sekolah itu berdiri untuk melayani beberapa teman yang tak bisa ditampung di sekolah negeri. Sebuah lembaga pendidikan yang telah menanamkan begitu banyak jasa. Itu yang membuatku termotivasi untuk ikut di salah satu gerakan pelajarnya. Jujur aku terpesona dengan kegigihan orang-orang Muhammadiyah yang telah memangkas semua hambatan di lingkungan kami untuk bersekolah. Aku sesungguhnya rindu dengan tindakan luar biasa ini. Sebuah tindakan yang kini sudah jarang aku temukan pada pewaris-pewarisnya
‘engkau ingat sekolahmu dulu? Aku lebaran kemaren sempat pulang dan banyak yang mengeluh betapa berubahnya sekolah itu. Kini ongkos masuknya melebihi sekolah negeri. Katanya ada kelas khusus unggulan yang patokanya adalah biaya dan kepandaian. Tapi yang terpenting adalah, biaya! Malahan sekarang disiplin keagamaanya mirip dengan sekolah-sekolah Islam Terpadu. Kau tahu sendiri kita ini tumbuh sama-sama di masyarakat religius. Tapi dulu kita tidak mengalami pemaksaan yang mengerikan dan bahkan bangunanya sekarang rapat dengan tembok-tembok tertutup. Kau pasti tahu lapangan tempat kita main sepak bola sekarang sudah disulap menjadi laboratrium komputer. Semua yang dulu membuat kita bisa berdekatan dan bergaul kini lenyap. Aku merasa kehilangan, entah kalau kamu’
Ya tiba-tiba aku terbang dalam ingatan masa lampau. Saat sekolahku dan sekolahnya tak ada pembatas. Kami bergaul rapat dan saling membantu dalam segala hal. Bahkan lapangan sepak bola itu menjadi milik bersama. Identitas sekolahku dan sekolahnya berbeda. Aku tinggal di sekolah swasta yang agak nasionalis dan ia belajar di Muhammadiyah. Tapi kami jarang sekali konflik. Biarpun berbeda kami tak pernah merasa kesal dan kecewa satu sama lain. Belajar butuh kebebasan intelektual dan pemahaman akan kemajemukan. Mungkin itu yang kini mulai dibangun dan coba ditegakkan dalam iklim sekolah inklusi Sebuah sekolah yang merayakan perbedaan dan memberikan ruang pada murid untuk memahami keaneka ragaman. Tampaknya identitas kini jadi perkara mendesak yang menggelisahkan banyak orang. Termasuk diri kawanku ini.
‘benar sekolah kita telah berubah. Tapi bukankah hidup ini memang harus berubah. Anakmu dan anakku pasti berbeda dengan semasa kecil kita dulu. Kalau kita dulu habiskan waktu main bola di halaman samping sekolah hingga petang lalu belajar mengaji di musholla bersama. Tapi sekarang tiap sore anakku harus kuantar untuk les renang, kadang piano dan bahasa asing. Aku ingin anakku berhasil melebihi diriku. Apalagi masa depan sulit untuk dibaca. Yang kutahu masa depan mensyaratkan kemampuan yang unggul dan aku tak ingin anakku kalah dalam kompetisi yang pasti akan terjadi nanti. Mungkin karena itu aku tak begitu peduli dengan apa yang kaukatakan hilang tadi’
Kulihat raut wajahnya yang gusar dan sepertinya tak percaya dengan apa yang baru saja dikatakanya sendiri. Balutan jas tuxedo itu seperti tempurung yang menutupi badanya. Tanganya diletakkan diatas meja sambil jarinya mengaduk-aduk jice apokat yang sejak tadi hanya dicicipi sedikit. Aku melihat ia tampak galau dan sedikit cemas. Ia sudah berubah, itu pendapatku.
Mungkin waktu atau pertemuan dengan dunia baru yang merubah kita. Sejak dulu pertanyaan itu menggelisahkanku. Apa yang sesungguhnya berperan besar dalam mengubah pandangan hidup seseorang? Aku kenal kawanku dulu sebaik aku kenal diriku; kami mengaji bersama, main bola bareng dan bahkan punya mimpi serupa. Kuingat cita-citanya adalah jadi sopir bus yang bisa membawanya kemana-mana. Sama denganku. Buatku seorang sopir adalah manusia petualang. Ia tahu kota yang terjauh dan belum pernah kami jamah. Kini pandanganku dan pandanganya sangat berbeda. Lebih mudah dikatakan saling bertabrakan. Ia berdiri persis dihadapan posisi yang kerapkali aku jadikan sasaran kritik. Seorang yang percaya kalau keunggulan intelektual adalah segalanya. Pendidikan sebaiknya berada pada posisi itu. Maka pandangan ini selalu percaya kalau seorang siswa adalah manusia tanpa potensi. Hanya melalui penanaman, pengajaran dan kedisplinan yang spartan baru mereka mampu meraih keunggulan. Sejumlah sekolah Muhammadiyah mengawali semangat pendidikan dengan karakter seperti itu saat ini. Seorang wali siswa yang anaknya sekolah disana bertutur kepadaku suatu saat:
‘anak saya terlambat masuk dan mendapat hukuman fisik. Saya sebenarnya ingin protes dan sempat mau bertanya kenapa masih melakukan tindakan seperti itu? Saya juga kadang ingin bertanya mengapa anak-anak harus pulang hingga larut untuk mendapat pelajaran tambahan yang banyak sekali jumlahnya? Saya kuatir kalau anak-anak kehilangan waktu dan kesempatan bermain karena sekolah padat dengan pelajaran. Saya bertanya untuk apa uang pendidikan mahal dan selalu saja ada yang dinamakan dengan uang gedung. Kadang saya bertanya ini sekolah untuk anak atau untuk para pengurus?
Mungkin komentar ini agak keterlaluan. Tapi soal biaya dan waktu pembelajaran memang jadi keluhan umum. Tak semua orang tua ternyata senang kalau anaknya sibuk di sekolah. Aku termasuk orang yang tak ingin anak lama di sekolah. Anak buatku tetap berada di bawah asuhan orang tua. Tanggung jawab dan kehangatan hubungan tak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh sekolah. Temanku punya pandangan yang mirip dengan tokoh dalam film I’m Not Stupid. Sebuah film yang cocok untuk mereka yang percaya akan pendidikan serius. Anak-anak Singapura yang begitu bebal terhadap sesama dan melihat kawan hanya merupakan pesaing kemampuan. Hidup mereka seperti dalam keadaan terus-menerus berlomba. Mereka saling berlomba. Dan kegagalan adalah sebuah celaan. Kesuksesan walau harus dibayar dengan ongkos sosial tinggi tetap dirasakan perlu. Alangkah mengerikanya pandangan temanku dan mungkin pandangan umum orang tua.
‘benar kawan mungkin kita punya pandangan berbeda dalam mendidik. Kau pasti ingat pak kyai Khasanuddin almarhum yang banyak sekali melatih kita tentang kehidupan. Kita tak pernah diingatkan dan dimarahi kalau lupa mengaji. Beliau tak pernah menghukum. Beliau hanya tak ingin kita hanya duduk berdiam diri. Engkau dan aku selalu disuruhnya melakukan apa saja yang bermanfaat. Katanya, menganggur itu dosa. Dan ketika kita diam membaca selalu saja pak kyai merasa enggan untuk mengganggu bahkan kita kadang diminta untuk menceritakan apa yang sudah kita baca. Satu hal yang diingatkan oleh beliau dan merupakan pesan nabi, jadilah orang yang bermanfaat’
Kulihat muka temanku seperti tergores ingatanya. Aku tahu dialah salah satu santri kesayangan pak kyai. Kawanku suka membaca dan pandai menjelaskan semua hal. Kufikir dulu dia akan menjadi seorang ilmuwan atau setidaknya dosen. Pesan menjadi orang bermanfaat itu kami praktekkan dalam sehari-hari. Pak kyai selalu meminta kami memberitahu tentang apa yang sudah kami lakukan buat membantu orang lain. Bahkan membantu menjemur pakaian tetangga sekalipun dipandang sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kini pendidikan bermanfaat itu kemudian dipraktekkan dengan alat ukur yang memalukan. Pendidikan harus bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat untuk pasar kerja. Jarang sekali pendidikan meyentuh sisi-sisi sosial yang bisa menempatkan seorang siswa dalam hubungan yang penuh makna. Kebermaknaan mungkin itu yang ditanggalkan oleh dunia pendidikan sekarang ini. Sesungguhnya pendidikan agama bisa meyentuh batas itu tapi jatuh gagal karena banyak bungkusan propaganda. Di sekolah Muhammadiyah tampaknya itu yang dijadikan siasat: membentangkan spanduk penerimaan sambil menyindir sekolah yang berbeda keyakinan. Tawaran toleransi ditenggelamkan oleh semangat fanatisme buta.
Seorang yang sangat populer, psikolog Austria, bernama Victor Frankl pernah mengatakan tentang kekuatan makna. Dikatakan olehnya, ‘pencarian seseorang akan makna adalah motivasi utama hidupnya….dan hanya dapat dipenuhi oleh dirinya sendiri…kita dapat menemukan makna dalam setiap bentuk dengan tiga cara yang berbeda (1) dengan menciptakan pekerjaan atau melakukan tindakan: (2) ….dengan menghayati sesuatu, misalnya alam atau kebudayaan atau,…dengan menghadapi ….manusia lain dalam keunikanya-dengan mencintainya….dan (3) melalui sikap kita menghadapi penderitaan yang tak terelakkan…makna masih bisa terdapat dalam penderitaan sekalipun
Kebermaknaan itu yang membuat pendidikan menjadi pematangan kedewasaan. Usai sudah sekolah yang hanya mengandalkan pola ‘hukum dan beri hadiah’. Keunggulan pribadi terbukti tak bisa memberikan insentif yang berarti bagi sebuah suasana sosial. Lebih-lebih di tengah petaka yang sepertinya tak pernah berakhir. Anak-anak kecil berusaha bunuh diri karena tak bisa bayar biaya pendidikan. Orang tua mengeluh karena semua harga barang-barang pokok terus naik. Susu, beras, minyak goreng bahkan air sekalipun diberi label harga. Dan pendidikan yang menjadi kebutuhan pokok tak bisa disentuh oleh mereka yang miskin. Jumlah resmi orang miskin 39,5 juta. Sebuah angka yang heboh untuk negeri yang merayakan ulang tahun kemerdekaan ke 62. Kini teman dihadapanku adalah lapisan sosial yang beruntung. Pengusaha dan politisi. Aku pun juga berada pada posisi beruntung. Pertanyaan yang mendesak diantara kami tak lain, bagaimana kami memberi manfaat untuk mereka yang kini banyak berposisi sebagai ‘tak beruntung’ ini?
‘ya aku kadang juga berfikir sama denganmu. Banyak anak-anak tak beruntung yang tak mampu sekolah. Tangan kita tak cukup kuat untuk memecah semua soal ini. Itu yang mengantarku untuk hidup di partai politik. Aku merasa punya tangan kuat untuk merubah kebijakan pendidikan yang selama ini kacau. Aku dapat memanggil menteri pendidikan untuk kutegur, kuperiksa bahkan kuadili. Cara ini kaunggap efektif untuk menyelesaikan kekusutan yang ada di lembaga pendidikan. Bukankah kau setuju dengan yang kulakukan. Lebih praktis dan langsung ada di jantung persoalan’
Akh temanku ternyata telah banyak berubah. Optimisme nya tentang partai mirip dengan kepercayaan kami waktu kecil. Kalau Superman itu ada dan mampu terbang hingga ke langit yang teramat tinggi. Rupa-rupanya ia aktivis partai yang tak pernah merasa ditegur oleh rakyatnya sendiri. Aku ingat dengan perkara tegur-menegur ini. Seorang bercerita padaku tentang pertemuan akbar di Muhammadiyah. Seorang menteri pendidikan yang berasal dari organisasi Muhammadiyah dikritik oleh kader muda yang gigih dan cerdas. Tanggapan dingin Mendiknas-yang bisa disebut kader Muhammadyah-menunjukkan betapa lemahnya disiplin organisasi ini. Kawanku seperti bermimpi, mengadili, bertanya, menyanggah kebijakan menteri. Mana mungkin jika Muhammadiyah sendiri, asal muasal pemegang kebijakan pendidikan, tak mampu untuk mengendalikanya. Tempat dimana Muhammadiyah lahir, Yogyakarta, menjadi contoh tauladan bagaimana komersialisasi dilangsungkan. Sekolah yang memang didedikasikan untuk orang-orang yang mampu. Bagaimanapun aku percaya, kalau cacat dunia pendidikan sekarang ini tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab Muhammadiyah. Baik sebagai organisasi maupun para kadernya
‘kaufikir dengan mengadili seorang menteri semua soal akan selesai. Kaufikir mudah untuk merubah kebijakan dengan tindakan panggil-memanggil. Mustinya organisasimu Muhammadyah itu bisa melakukan langkah drastis. Menggratiskan pendidikan pada semua sekolah dasarnya, bukanya malah membuat mahal. Daftar ulang membayar, ujian membayar, piknik bayar lagi…semuanya berduit. Bahkan ada uang infak yang jumlahnya sudah ditentukan…itu namanya apa kalau tidak jual beli agama! Coba aku ingin tanya mana di kepulauan ini yang sekolah Muhammadiyah nya gratis? Tak malukah kalian dengan sekolah orang Tionghoa yang sudah 50 tahun membuat sekolah gratis. Tak malukah kalian dengan sekolah Dompet Dhuafa yang juga gratis? Rumah Zakat yang baru berusia muda yang juga buat rumah bersalin gratis? Gratis itu komitmen paling dini kawan untuk mengukur keberpihakan pada sesuatu yang kini diperlakukan secara komersial…maafkan aku jika aku agak kasar, mungkin aku terlampau berharap berlebihan terhadapmu. Aku tak ingin engkau seperti orang mapan yang punya banyak rasa takut, kehilangan inisiatif dan tak memiliki imaginasi’
Aku tiba-tiba ingin pulang kembali ke rumah. Pertemuan ini rasanya berjalan sia-sia dan berakhir dengan kepedihan. Aku panik karena kuatir kata-kataku terlampau tajam untuk didengar. Apa yang biasa kusampaikan di depan anak-anak muda tentu tak patut jika kukatakan dihadapan kawanku yang mapan dan sudah agak ubanan ini. Kutahan semua kegeramanku pada organisasi yang banyak melahirkan para pemuka dan penguasa. Presiden pernah memberi nasehat keliru, agar Muhammadiyah juga berperan sebagai kekuatan wirausaha tak hanya pendidikan. Padahal bagiku, pendidikan adalah kekuatan strategis dan terpokok dalam mengeluarkan bangsa ini dari lubang derita. Peran Muhammadiyah dalam pendidikan sepatutnya dihargai dan didorong dengan lebih optimal. Kalau pendidikan beres maka semua hal bisa diraih. Termasuk ekonomi. Apalagi kalau hanya menjadi wirausaha. Kembali Presiden menunjukkan jalan berfikir yang dangkal dan rapuh.
‘maaf jika aku menyinggungmu. Aku tak ingin pertemuan ini menjadi sebuah pertikaian yang tak berarti. Persahabatan kita lebih dalam ketimbang kedudukan kita saat ini. Aku sekali lagi minta maaf. Salam buat istrimu dan anak-anak. Aku kebetulan ada diskusi siang ini. Jika tak keberatan aku meminta alamat dan nomor HP mu. Maafkan aku kawan’
Kujabat tanganya dengan terburu-buru. Ia memberi nomor HP yang segera kucatat. Kujabat tanganya erat. Tiba-tiba ia memelukku erat
‘kawan kau sadarkan aku yang telah lama tenggelam. Aku punya pandangan sama denganmu. Hanya aku mungkin orang penakut yang kuatir akan perubahan cepat. Maafkan aku juga’
Ia tampak agak gugup dan tercengang. Diundurkanya kursi sambil berdiri dan menatapku agak lama. Ia berdiri dalam wajah yang lemah dan letih. Aku tahu aku telah membangunkan sesuatu yang telah lama terlelap dalam dirinya. Sebuah keyakinan yang dulu membuat kami terikat satu sama lain. Keyakinan yang membuat kita percaya akan kebesaran dan kekuatan negeri ini.
Kami bersama-sama meninggalkan rumah makan itu. Ia menawariku menumpang mobilnya. Kubilang aku membawa motor dan mengucapkan terimakasih atas tawaranya. Kami bersama –sama meninggalkan rumah makan yang mulai didatangi pengunjung yang ingin menuntaskan akhir pekan. Aku susuri jalan sambil mengingat-ingat kembali gugatanku pada pendidikan di Muhammadiyah. Sebuah gugatan yang dulu juga pernah dilampiaskan oleh Paulo Freire. Pendidikan yang membebaskan adalah konsep yang ditawarkanya. Freire. Pendidikan yang berusaha menanamkan kesadaran tentang realitas sosial. Di mata Freire seorang anak memiliki dan mempunyai kesadaran ganda. Kesadaran tentang diri dan kelas sosialnya. Melalui pendidikan seorang anak akan mengalami transformasi pengalaman yang bermakna. Untuk bisa lebih kritis atas sistem yang membelenggunya. Kemarahanku sama halnya dengan yang dikatakan Ivan Illich, seorang revolusioner pendidikan, yang mengatakan kalau selama ini pendidikan hanya mengemban tiga fungsi: 1) sebagai gudang mithos masyarakat 2) pelembagaan kontradiksi-kontradiksi yang dibawa oleh mitos tersebut 3) sebagai locus ritual yang mereproduksi serta menyelubungi perbedaan-perbedaan antara mithos dan realitas.
Mithos itu yang telah mengabaikan kesadaran kritis dan akal sehat pada para peserta didik. Mereka seperti kumpulan domba yang dicangkokkan dan digiring untuk bertindak sebagaimana yang diperintahkan. Di pinggir jalan ada sejumlah bimbingan belajar yang hanya mengajari anak menjawab soal, bukan bertanya. Pertanyaan kini jadi kecurigaan dan tampak mengkuatirkan. Tapi anak-anak yang dibesarkan di lingkungan naif ini bersemangat dan gemar untuk ikut dalam pasukan menjawab soal. Mereka yakin masa depan ada di tangan jenis spesies seperti itu. Jika begitu benarlah kritik yang selama ini dihadapkan pada pendidikan tradisional, yang tidak mampu memberikan kebebasan dan kepercayaan diri pada anak didiknya.Idam-idaman pada pendidikan progresif. sekarang ini baru batas mimpi dan sedikit sekolah yang berani melakukanya. Mungkin karena para guru enggan kehilangan wibawa atau sekolah kemudian jadi mirip sangkar arena bermain.
Kulewati sekolah Muhammadyah yang populer dan diburu-buru oleh banyak orang. Tembok tinggi menutup badan sekolah hingga tampak mirip penjara. Kadang aku bertanya siapa murid yang ada di dalamnya? Murid-murid yang pasti tak terlampau berani menatap keluar karena dibiasakan berpandangan sempit dan terbatas. Jalanan aspal itu hanya tampak kalau murid mau memanjat ke dinding dan mungkin itu akan disebut pelanggaran. Seorang murid yang ideal jaDI tampak kelihatan tua karena hanya mensyaratkan sikap diam, patuh dan tak pernah melanggar ketentuan sekolah. Sebuah ketentuan yang disusun untuk menertibkan dan mengelola sebuah fikiran. Alangkah mengerikanya sekolah semacam ini! Sebuah sekolah yang benar-benar mengadopsi ketertiban secara berlebihan. Anak-anak seperti boneka yang kebebasanya hanya diserahkan pada ketentuan dan kewajiban sekolah. Ini situasi yang tidak hanya dialami oleh sekolah Muhammadyah sendirian.
Semua sekolah kini seperti melakukan klaim yang mengerikan. Mereka bukan hanya mendidik tapi juga menghukum anak-anak didik untuk bisa memiliki kemampuan melebihi usianya. Gagasan pendidikan tradisional diambil alih dengan cara yang dramatis. Sebuah pendekatan yang selalu menilai anak punya potensi masalah ketimbang harapan. Pendidikan yang selalu melihat anak seperti ember kosong yang harus ditumpahi segalanya: pengetahuan, informasi, pengalaman dan pembelajaran. Syarat pendidikan berhasil adalah kemampuanya bisa diterima dan diakui oleh pasar kerja. Bahkan untuk disebut sekolah unggulan, ciri pertamanya adalah kemampuan berbahasa Inggris
. Tentu yang menjadi imbas pertama-tama adalah pembebanan biaya. Walau ada beberapa sekolah yang malahan gencar berkampaye biaya murah. Sebuah perguruan tinggi malahan membuat iklan yang mengenaskan: cukup dengan Rp 860.000 bisa kuliah loh! Seakan-akan pendidikan adalah pengalaman untuk meraih status, ijazah dan tentu gelar. Tak aneh jika seorang gurbenur mendapat penghargaan doktor karena tak mampu mengatasi banjir dan kemacetan. Ada bupati yang dapat gelar doktor dan kini sedang terancam untuk dimasukkan ke bui. Gelar hanya sebuah cara untuk meraih sesuatu yang nyatanya dapat dibeli dan ditukar dengan posisi politik. Betapa suramnya wajah pendidikan yang mulai kehilangan daya gugat, daya kritik dan sudah barang tentu, kemampuan untuk menggugat.
Di jalan beberapa spanduk tampak bertebaran. Sebuah sekolah Muhammadiyah membuka pendaftaran murid baru. Berdampingan dengan kata-kata promosi ada nama penerbit yang menjadi sponsor. Pemandangan umum dimana-mana. Penerbitan buku menjadi salah satu pendukung di spanduk. Mungkin ini semacam pengukuhan atas apa yang biasa dikeluhkan. Tentang aroma pendidikan yang berbau uang dan persekongkolan. Sekolah telah jadi tempat bergabungnya semua kepentingan. Ada uang seragam, daftar ulang, piknik, gedung dst. Tak habis-habis uang dikuras. Terutama untuk buku yang pekan-pekan ini diguncang berbagai isu-isu yang tak jelas. Bakar-bakar buku yang dilakukan oleh Kejaksaan mengingatkan kembali apa yang dulu dilakukan oleh pasukan Mongol. Ringkasnya pendidikan kemudian hanya jadi tempat dimana hukum jual-beli berlaku dengan cara serampangan. Aku memang hanya bisa melakukan kritik, mengurut dada perlahan dan kini mulai membuat sekolah tandingan. Tujuanku hanya satu, bagaimana membuat pendidikan jadi urusan yang lebih tinggi ketimbang kecerdasan dan meluluskan UAN. Pendidikan adalah jalan untuk meretas masa depan yang lebih baik sekaligus bersahabat. Sayangnya pendidikan memang kini hilang dari urusan penting negara. Negara turut campur untuk soal yang semustinya memberi banyak kebebasan. Soal kurikulum, soal penertiban guru hingga bagaimana mendirikan sekolah tampaknya menjadi kegemaran negara.
Motorku memasuki pelataran perumahan. Di samping pos satpam kulihat anak-anak kampung bermain layangan. Kakinya yang hitam dan gelap menandakan betapa banyak sudah tanah yang mereka injak. Rambut acak-acakan dan merah. Sinar matahari seperti memanggang kepala mereka. Wajah-wajah kusut yang mengeluarkan peluh ini kelak hanya akan menjadi barisan pengangguran. Jika tak ada pendidikan bermutu yang meyentuhnya. Andai tidak ada sekolah murah yang orangtuanya sanggup untuk menanggung. Kalau tak ada tangan organisasi keagamaan yang mulai berani meyentuh dan bertindak terhadap mereka. Kalau melihat mereka, aku tiba-tiba ingat KH Akhmad Dahlan. Seorang ulama yang pasti mendirikan organisasi Muhammadyah, diantaranya karena alasan sederhana. Membuat pendidikan rakyat yang mampu membantu mereka yang fakir dan terlantar. Kini masih banyak orang-orang miskin sebagaimana pada masa hidup beliau. Yang tidak ada adalah sosok seperti KH Akhmad Dahlan yang berani menanggalkan kepentingan pribadi untuk terlibat dan memprakarsai gerakan yang berdiri tegak membela kepentingan mereka yang lemah. Mungkinkah anak-anak muda IRM mampu membawa api semangat beliau? Aku agak malu untuk menjawabnya!
Disampaikan untuk acara IRM, 17 Agustus 2007. Sekali lagi jangan tersinggung dengan judul ini, karena sesungguhnya saya sangat kagum dengan Muhammadyah. Kekaguman yang membuat saya melakukan kritik dan harapan besar untuk organisasi yang rasa-rasanya sudah berusia udzur ini.
Penulis bebas dan seorang yang banyak punya teman yang sekolah di Muhammadyah maupun yang duduk dan menjadi pengurus disana.
Inilah kaidah Rumah Pengetahuan Amartya di bawah ikatan semboyan: Belajar untuk Berpihak dan Membela yang Lemah
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa struktur keluarga yang terjamin stabilitasnya adalah struktur keluarga tradisional, struktur komplementer. Suami misalnya, memainkan peran sebagai pencari makan, pencari nafkah atau pekerja social lainnya. Istri berperan sebagai ibu rumah tangga, yang memelihara anak, yang mengerjakan pekerjaan rumah. Lih Jallaludin Rakhmat, SQ For Kids, Mizan 2007
Di Indonesia sekolah Inklusi relative baru yang berpandangan akan kemajemukan adalah potensi utama dalam dasar-dasar pendidikan. Disana tak ada perbedaan kemampuan, kebangsaan dan agama anak. Semua dianggap memiliki potensi yang sama dan sebaiknya seorang anak tumbuh dalam kemajemukan seperti itu. Di Jogjakarta salah satu sekolah yang menerapkan prinsip inklusi adalah SD Tumbuh, agak mahal tetapi menarik dalam pengelolaan kurikulum.
Sebuah pendekatan tentang kemanfaatan itu ada dalam methodology yang kini baru diperkenalkan yakni Contextual Teaching & Learning yang mengangkat dua pertanyaan pokok: ‘konteks-konteks apakah yang tepat untuk dicari oleh manusia? Dan langkah-langkah kreatif apakah yang harus saya ambil untuk membentuk dan memberi makna pada konteks?. Sistem CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, social dan budaya mereka. Lih Elaine B Johnson, Contextual Teaching & Learning, MLC, 2007
Lih Elaine B Johnson, PH.D, Contextual Teaching & Learning, MLC, 2007
Lih HAR Tillar, Manifesto Pendidikan Nasional, Kompas, 2005
Pedagogik Transformatif berupaya menstransformasikan potensi yang ada pada diri seseorang karena dia itu sebagai makhluk yang bebas, dan dengan menstransformasikan dirinya dia dapat menstransformasikan lingkunganya, adat-istiadatnya, lenbaga-lembaga masyarakat yang dimilikinya.
Gagasan pendidikan tradisional berangkat dari tesis (1) tidak ada teori yang dirumuskan secara koheren yang membahas kegiatan belajar dalam system pendidikan tradisional (2) motivasi didasari ganjaran, hukuman atau hadiah dan persaingan (3) belajar dengan menghapal dan menyimpan informasi tanpa bantuan catatan (4) modifikasi prilaku jadi dasar pembentukan system pendidikan (5) kurikulum tersembunyi menjadi dasar dalam kehidupan pelajar (6) modus dominant: guru bicara Lih Paulo Freire (editor) Menggugat Pendidikan, Pustaka Pelajar, 1999
Untuk sekolah yang dikategorikan unggulan akan mendapat dana Rp 300 juta per tahun. Sekolah Bertaraf International (SBI) menekankan beberapa cirri: (1) penyediaan sarana sekolah yang ramah tekhnologi serta model pembelajaranya menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar (2) TOEFL guru minimal 500. Kedua syarat ini yang mengantarkan 200 sekolah masuk kategori SBI dan sialnya belum ada kurikulum maupun Standarisasi yang jelas dari pemerintah. Tempo 19 Agustus 2007
Gurbenur DKI (yg sudah berhenti) Sutiyoso dapat gelar Doktor dari Universitas Diponegoro dan Bupati Kutai Kartanegara juga mendapat gelar Doktor
Mendiknas Bambang Soedibyo pada tanggal 5 Juli 2006 kirim surat kepada Jaksa Agung untuk melarang peredaran buku-buku sejarah yang menurutnya memutar-balikkan fakta yang kemudian membuat Kejaksaan melarang 13 buku pelajaran Sejarah yang diterbitkan oleh Erlangga, Yudhistira, Exact dan Grasindo. Buku itu diantaranya, Kronik Sejarah, Pengetahuan Sosial, Sejarah kelas II dan kelas III SMP, sejarah nasional dan umum untuk Tingkat SMA. Dasar Kejaksaan adalah UU Nomor 16/2004 dan UU Nomor 4/Pnps/1963 tentang Pengamanan Barang. Lih Tempo 19 Agustus 2007
Ada dua produk UU dalam system pendidikan kita (1) UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dalam banyak pasal menetapkan tentang syarat-syarat pendirian sekolah yang begitu detail dan tidak membuka kemungkinan hadirnya sekolah alternative (2) UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen yang mengatur tentang standar guru. Dengan ketetapan yang penuh bersyarat itu mengingatkan kembali akan sikap pemerintah Hindia Belanda yang mengeluarkan Onderwijs Ordonantie (Undang-Undang Sekolah Liar) yang melarang pendirian sekolah di luar sekolah colonial dan kemudian ini ditentang oleh Ki Hadjar Dewantara, Lih Kompas 13 Agustus 2007
This entry was posted
on 01.31
.
You can leave a response
and follow any responses to this entry through the
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.
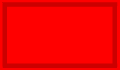


0 komentar